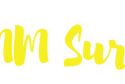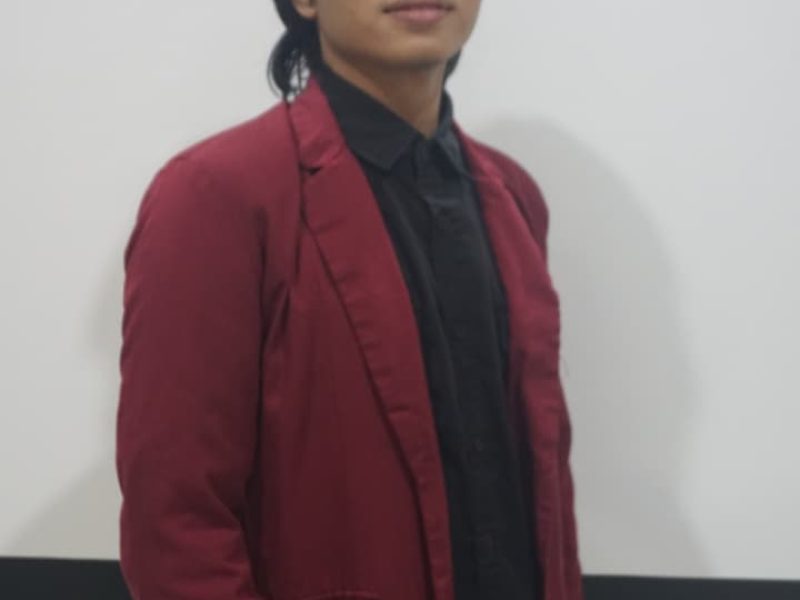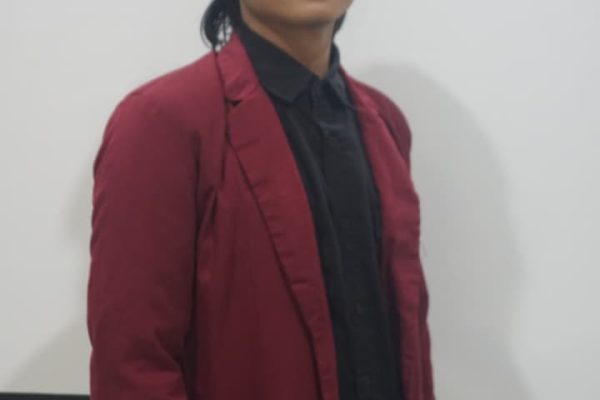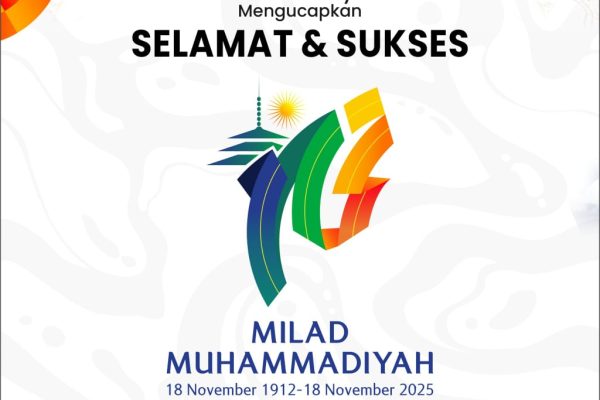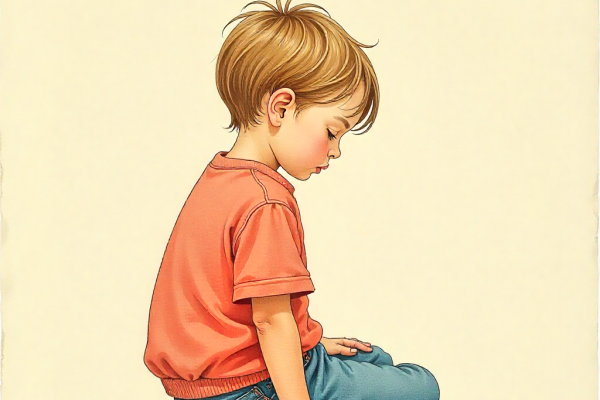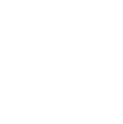Oleh: Balqis Saila Sufa Al Zakiyah – Ketua Umum PK IMM Buya Hamka Fisip Unair
Surabaya – Salah satu dari beberapa permasalahan yang terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia adalah masalah pengangguran. International Monetary Fund atau IMF tahun 2025 menyebutkan dalam laporannya bahwa Indonesia telah menempati posisi pertama di ASEAN dengan tingkat pengangguran tertinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran Indonesia per Februari 2025 naik sebanyak 7,28 juta orang (Kompasiana, 2025).
Meski dalam catatan milik BPS dituliskan bahwa terdapat tambahan 3,59 juta orang atau 1,11 persen dari Februari tahun 2024 lalu, tetap tak dapat dipungkiri bahwa angka pengangguran masih meraih angka yang cukup besar di Indonesia saat ini (BPS, 2025).
Menurut Pasal 34 UUD 1945, pemberdayaan rakyat miskin adalah tanggung jawab negara. Tak hanya itu, negara juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang tidak mampu (Kumparan, 2023). Sehingga dalam hal ini, negaralah yang bertanggung jawab menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
Maka, tingginya angka pengangguran merupakan bukti kegagalan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sayangnya, masalah pengangguran hanyalah salah satu dari rangkaian kegagalan negara yang memengaruhi hampir setiap lapisan kehidupan masyarakat. Tanpa kita sadari, banyak fenomena yang kita temui adalah dampak dari keputusan negara.
Dampak dari Keputusan Negara
Mari coba kita urutkan dampak dari keputusan negara itu dari pagi hingga malam:
Sejak pagi hari ketika bersiap membuat sarapan, masyarakat dihadang oleh realita keras, yakni harga bahan pokok yang meroket. Di Jawa Timur, misalnya, cabai rawit tembus Rp 63.500/kg, naik lebih dari 16% dibanding sebelumnya, sementara minyak goreng, daging, dan bahan lainnya juga ikut melambung (Detik, 2025).
Siapa yang bertanggung jawab atas inflasi seperti ini? Bukankah ini tanda lalainya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok?
Kemudian, setelah sarapan, perjalanan menuju kantor menjadi ujian berikutnya. Kemacetan seolah menjadi menu harian masyarakat. Di Surabaya, misalnya, yang sering dibanggakan sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, hiruk-pikuk jalanan dipadati kendaraan pribadi akibat minimnya transportasi publik yang efisien, urbanisasi yang tinggi dan kurangnya kebijakan pengendalian mobilitas.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) GNFI Batch 7 dengan topik Applied Data Analyst & Visualization for Digital Journalism, ditemukan bahwa terdapat 39% masyarakat mengeluhkan kemacetan meski sudah menggunakan transportasi umum, dan mayoritas responden menilai jadwal serta fasilitasnya tidak memadai (Goodstats.id, 2024).
Kondisi ini bila terus-menerus akan membuat masyarakat terjebak dalam kerugian waktu, energi, dan produktivitas. Biaya sosialnya tidak kecil, seperti terlambat bekerja, stres berkepanjangan, bahkan kehilangan peluang hidup yang lebih baik.
Ini merupakan konsekuensi dari kelambanan negara dalam merancang dan menata transportasi publik yang layak dan terintegrasi. Lagi-lagi, ini dampak dari keputusan negara.
Kemudian, masalah tak berhenti begitu saja. Terdapat pula masalah klasik yang entah mengapa tak kunjung terselesaikan di banyak sudut kota, yakni masalah pencahayaan jalan di malam hari. Minimnya penerangan jalan bukan hanya soal estetika kota yang suram, tapi juga membuka celah bagi tindak kriminalitas dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Respon Pemerintah
Di tengah gelapnya jalanan, masyarakat seakan juga berjalan dalam kegelapan data dan janji. Setiap saat, masyarakat dihadapkan pada realita yang berulang: laporan inflasi yang terus naik, transportasi publik yang stagnan, dan angka kemiskinan yang tak kunjung turun. Realitasnya, kesejahteraan dan akses dasar masih jauh dari kata layak untuk didapatkan masyarakat.
Menyikapi berbagai masalah tersebut, tak jarang muncul pernyataan dari pejabat yang hanya berupa kalimat-kalimat normatif yang semakin didengar semakin hambar.
Bahkan, juga muncul kalimat yang tak layak dianggap sebagai respon dari pemerintah terhadap permasalahan publik. Misalnya, pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini, Bahlil Lahadalia, yang meminta masyarakat untuk bersyukur dalam menghadapi permasalahan yang ada. Respon tersebut muncul ketika dirinya diminta untuk menanggapi kritik masyarakat terkait minimnya lapangan kerja di Indonesia (Democrazy, 2025).
Pernyataan dengan frasa “kita harus tetap bersyukur,” seakan tak asing ditemui dalam setiap kegagalan negara menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan publik. Baik itu dikatakan oleh pejabat publik maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Rasa syukur yang sejatinya adalah nilai spiritual dan etis justru kerap dipelintir menjadi alat untuk menekan kesadaran kritis. Bahkan, ketika ada warga yang mempertanyakan kinerja pemerintah, tidak jarang ia dicap tidak tahu diri, tidak cinta tanah air, atau kembali pada frasa tidak bersyukur.
Padahal dalam ajaran Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al Ibrahim Ayat 7. Syukur bukan sekedar menerima, melainkan mengakui nikmat Allah dengan kesadaran. Lalu mengelola nikmat itu dengan cara yang benar dan adil dengan tujuan yang lebih besar, yakni kebaikan bersama.
Maka dari itu, sangat wajar bila masyarakat mengeluh, mempertanyakan, atau bahkan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas hak-hak yang seharusnya diperoleh. Justru bentuk rasa syukur tertinggi adalah ketika masyarakat sadar akan haknya dan menjaga agar negara tidak melenceng dari tugasnya sebagai pelayan publik.
Partisipasi Rakyat
Pada paradigma Human Rights-Based Approach (HRBA) yang dituliskan dalam The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (2025), negara merupakan duty bearer atau pemangku kebijakan yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kritik masyarakat terhadap pemerintahan, termasuk kebijakan-kebijakan dan pelayanan publik yang buruk, bukan hanya sah tetapi juga diperlukan.
Sebab dalam paradigma HRBA, partisipasi rakyat adalah inti dari sistem demokrasi agar negara tetap berada dalam koridor tanggung jawabnya.
Lebih jauh lagi, Hobbes, Rousseau dan Locke pun menegaskan bahwa negara negara lahir dari kontrak di mana rakyat menyerahkan sebagian kebebasan untuk perlindungan dan pelayanan ke pemerintahan (Pace & Gabel, 2025). Sehingga, negara disebut sah sebagai negara sejauh kemampuannya dalam menjalankan kontraknya yakni untuk melindungi hak dan kepentingan rakyat.
Pemikiran tersebut dituangkan dalam teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa jika negara gagal atau menyimpang, maka rakyat bukan hanya berhak, tetapi berkewajiban untuk mengoreksi dan menuntunnya kembali kepada jalur yang benar (Peters, 2011).
Oleh karena itu, meminta hak kepada negara merupakan bentuk tertinggi dari warga negara yang memahami posisi dan relasi kuasa dalam sistem politik. Kita bukan rakyat yang tunduk membabi buta demi stabilitas semu. Kita sebagai pemegang hak atau right holder adalah pemilik sah dari kontrak sosial itu sendiri.
Jadi, ketika ada yang menghardik kita agar bersyukur saja dan tidak banyak menuntut. Penting untuk diingat bahwa bersyukur dalam konteks kebangsaan bukan berarti membungkam diri atas penderitaan yang sistemik. Sebaliknya, rasa syukur itu terwujud saat kita sadar akan hak yang kita miliki, serta memperjuangkannya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang lebih rentan dan kerap disingkirkan dari ruang politik dan ekonomi.
Sebab diamnya satu individu, bisa menjadi kesunyian kolektif yang melanggengkan ketidakbertanggungjawaban oleh negara.
Kini, di tengah riuh rendah janji pembangunan dan jargon “Indonesia adalah negara besar,” masyarakat perlu mengingat satu hal penting. Negara bukan rumah ibadah yang harus disakralkan, melainkan bangunan sipil yang harus terus diuji daya tahan dan ketulusannya.
Kritik adalah bentuk cinta; protes adalah wujud keterlibatan.
Jika negara merasa cukup hanya dengan menyebut angka dan program. Sementara masyarakatnya tetap dihimpit tingginya harga bahan pokok, akses pendidikan mahal, dan pelayanan publik yang tak layak. Maka suara masyarakat adalah satu-satunya hal yang dapat menyadarkan mereka. Suara masyarakat adalah mekanisme pemulihannya.
Seperti dikatakan oleh Paulo Freire, seorang filsuf asal Brasil, dalam karyanya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed (2014). Mereka yang memiliki kekuasaan tidak akan menyerahkannya secara sukarela. Ia harus dipertanyakan, diawasi, dan—jika perlu—dipertaruhkan. (*)