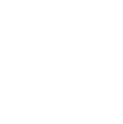gambar diunduh melalui freepik.com
Oleh : Muhammad Sayyid Mushaddaq – Ketua Bidang Kader PC IMM Kota Surabaya
Dalam beberapa waktu terakhir, kita kembali diguncang berita-berita tentang bullying di lingkungan pendidikan. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kasus-kasus tragis muncul silih berganti. Ada anak yang terluka fisik, ada remaja yang depresi, ada mahasiswa yang terisolasi secara sosial, ada pekerja muda yang secara perlahan tersingkirkan, bahkan yang paling parah ada yang sampai kehilangan nyawanya atau melakukan tindakan ekstrem. Kasus yang terjadi di Jakarta baru-baru ini hanyalah salah satu dari banyak sinyal bahwa ada yang sangat keliru dengan ekosistem pendidikan kita.
Namun di balik semua kegaduhan itu, ada satu hal yang sulit kita akui, masalah ini tidak berdiri sendiri, dan tidak hanya dilakukan oleh segelintir individu. Bullying menjadi marak karena kita semua secara sadar atau tidak membiarkannya hidup. Ya! kita semua yang berperan dalam menciptakan ruang akademik yang tidak selalu aman, tidak selalu sehat, dan tidak selalu manusiawi.
Pemerintah sering mengeluarkan regulasi, kampanye, dan pedoman pencegahan. Namun realitas di lapangan selalu lebih keras daripada teks peraturan. Banyak sekolah tidak memiliki konselor yang memadai, banyak kampus hanya memasang spanduk anti-kekerasan tanpa mekanisme penanganan yang berpihak pada korban, dan di tempat kerja, pelatihan lingkungan bebas perundungan kerap dilakukan sekadar memenuhi formalitas tahunan. Kebijakan ada, tetapi kehadirannya tidak selalu terasa.
Di sekolah, bullying mungkin tampak paling jelas intimidasi fisik, ejekan, pengucilan. Namun di kampus, bentuknya berubah menjadi lebih halus senioritas yang berlebihan, perploncoan yang dibungkus romantisme “pembentukan mental”, tekanan akademik yang tidak sehat, hingga kekerasan psikologis yang sulit diukur tetapi nyata meninggalkan luka. Sementara di ruang kantor yang penuh jargon profesionalisme, bullying muncul dalam wajah yang lebih rapi komentar merendahkan yang dianggap bercanda, persaingan tidak sehat, isolasi sosial, dan microaggression yang terjadi hampir setiap hari.
Pendidik, dosen, dan atasan tentu tidak bisa dipukul rata. Banyak dari mereka yang berjuang keras menciptakan ruang aman. Tetapi ada pula yang menertawakan keluhan, menganggap kekerasan sebagai bagian dari pembelajaran, atau bahkan ikut memperkeruh suasana melalui kata-kata maupun sikap. Bahkan ironisnya ada yang berupaya dengan segala cara menutupinya dari mata orang-orang hanya untuk menjaga reputasi instansinya. Ketika mereka yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi sumber keterlukaan, hilanglah makna moral dari ruang akademik itu sendiri.
Di sisi lain, keluarga yang seharusnya menjadi pelindung sering hadir secara fisik tetapi absen secara emosional. Kita terlalu fokus pada nilai, ranking, atau pencapaian karier, tanpa menyadari bahwa anak, remaja, atau bahkan orang dewasa membawa pulang luka-luka yang tidak pernah terlihat di atas kertas. Ketika ada kasus, sebagian orang tua justru defensif, berlindung di balik gengsi keluarga dan menolak melihat bahwa mungkin ada yang salah dalam pola pendidikan di rumah.
Yang terakhir tak kalah ironisnya, masyarakat (kita) menjadi penonton setia tragedi ini. Setiap kali ada kasus viral, kita ramai-ramai mengutuk, membagikan video, atau menulis komentar panjang. Namun setelah beberapa hari, semuanya tenggelam begitu saja. Kita marah, tetapi tidak bergerak. Kita bersimpati, tetapi hanya sebentar. Kita lebih menyukai sensasi daripada solusi.
Yang paling menyakitkannya adalah ketika kita bercermin dan menyadari bahwa kita juga bagian dari masalah ini. Kita pernah menertawakan candaan yang melewati batas. Kita pernah diam ketika seseorang direndahkan. Kita pernah melihat senioritas toxic dan menganggapnya tradisi. Kita pernah menganggap komentar pedas sebagai hal biasa. Kita pernah membiarkan ketidakadilan terjadi hanya karena “bukan urusan kita”.
Bullying tidak lahir dari satu pelaku. Bullying lahir dari budaya budaya yang dibentuk oleh pembiaran, ketidakpekaan, dan kebiasaan menormalisasi kekerasan. Dan budaya itu dibangun oleh kita semua, di setiap ruang: ruang kelas, ruang kuliah, ruang rapat, organisasi, hingga obrolan kecil sehari-hari.
Jika kita benar-benar ingin menghentikan siklus ini, maka perubahan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah, kampus, atau kantor. Kita semua punya tanggung jawab untuk terlibat. Sudah saatnya kita memandang manusia sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek untuk menunjukkan superioritas, sarana bersaing, atau tempat melampiaskan sesuatu. Kita perlu menciptakan lingkungan akademik yang benar-benar aman, bukan hanya sebatas slogan, tetapi tercermin dalam tindakan nyata.
Setiap korban bullying adalah cermin kegagalan kolektif. Dan perubahan sejati hanya akan dimulai ketika kita berhenti menunjuk satu sama lain, lalu mulai menengok ke dalam diri sendiri bertanya dengan jujur: apakah saya sudah menjadi bagian dari solusi, atau justru bagian dari masalah?
Editor: Muhammad Syafril Harsya