Oleh: Syafril Harsya – Ketua LSO Cendekiawan Institute PC IMM Kota Surabaya
Surabaya – Di negeri ini, kebenaran sering diperlakukan seperti hidangan prasmanan. Ambil yang terlihat enak, buang yang terasa pahit. Pilihan dibuat bukan berdasarkan nilai gizi atau kebenaran itu sendiri, tetapi semata karena rasa yang cocok di lidah.
Fenomena ini semakin nyata pada tahun 2025, ketika Indonesia diguncang protes besar bertajuk #IndonesiaGelap. Mahasiswa dan rakyat memenuhi jalanan, menuntut kejelasan arah, kebijakan yang transparan, dan terutama, kebenaran.
Tuntutan mereka sederhana: kebijakan tidak boleh turun begitu saja dari meja kekuasaan. Harus diuji dengan fakta, ditimbang dengan data, dan disaring lewat logika. Namun di tengah panas matahari yang menyengat, diiringi bunyi klakson dan teriakan, yang terlihat justru paduan antara simbol perlawanan dan budaya pop.
Ada bendera bajak laut One Piece yang berkibar di antara massa, sebuah simbol yang, bagi sebagian orang, melambangkan semangat kebebasan dan perlawanan bersanding dengan meme satir dari media sosial dan poster-poster penuh ironi.
Fenomena ini mengingatkan pada pesan Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise diterjemahkan di sini menjadi Matinya Kepakaran. Nichols memperingatkan, pengetahuan yang dibangun bertahun-tahun kini sering kalah oleh opini instan, meme viral, atau narasi yang hanya memuaskan selera pendengarnya. Seperti prasmanan, orang bebas memilih “kebenaran” yang mereka mau, tanpa peduli apakah itu benar atau sekadar cocok dengan selera.
Donald Trump pernah menyebut media sebagai enemy of the people. Di Indonesia, jarang ada yang bicara seterang itu, tapi praktiknya mirip: pakar dibatalkan hanya karena tidak sesuai selera politik. Kabar yang terasa “manis” langsung dibagikan, meski sumbernya kabur atau sudah dibantah. Kebenaran jadi seperti lauk di meja prasmanan: siapa pun bebas ambil atau lewatkan, tergantung selera.
Akses Bukan Jaminan
Pada bulan ini Agustus 2025, jejak digital kita semakin padat. Pemerintah membahas cetak biru AI nasional. UNESCO bersama MAFINDO meluncurkan Social Media 4 Peace Phase II untuk mengajarkan literasi media di sekolah. Bahkan ada wacana pembatasan usia minimal pengguna media sosial. Semua ini mengakui satu hal: akses informasi saja tidak cukup, kita butuh kemampuan berpikir kritis agar tidak salah memilih “menu” kebenaran.
Namun, di lapangan, cerita berbeda. Program literasi digital memang ada, tetapi hoaks dan rumor tetap berlari lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah isu bisa menjadi “kebenaran” hanya dalam hitungan jam, bahkan sebelum jurnalis sempat memeriksa.
Kadang, simbol budaya pop seperti bendera bajak laut One Piece justru menjadi pemersatu massa. Ia menghadirkan bahasa visual yang mudah dipahami, membangun rasa kebersamaan di tengah kerumunan. Efeknya memang bisa lebih cepat memicu respons massa dibanding paparan data resmi, bukan karena data tak penting, tapi karena simbol dan cerita mampu menjangkau hati lebih cepat.
Nichols menulis, masalahnya bukan hanya orang kekurangan informasi yang benar. Masalahnya, banyak yang bersedia membela informasi yang salah sambil menutup diri dari koreksi. Fenomena yang ia amati di Amerika ini ternyata bergema di Indonesia, hanya berbeda kostum dan panggung. Di media sosial kita, berita bohong yang sesuai keyakinan politik menyebar cepat. Data kredibel sering diabaikan, bukan karena salah, tetapi karena tidak memanjakan selera.
Kita sedang menghadapi krisis ganda: krisis informasi dan krisis kepercayaan. IHSG merosot, skandal besar mengguncang BUMN, dan protes mahasiswa membara. Publik semakin mudah tergoda narasi instan, semakin sedikit waktu untuk memeriksa, semakin cepat percaya. Tanpa fondasi berpikir yang kokoh, bentuk paling dasar dari kepakaran, kita seperti tamu prasmanan yang memilih berdasarkan warna makanan (apa yang nampak dipermukaan), bukan isinya (mengulik sampai dalam).
Bahaya ini kian besar ketika ruang diskusi publik berubah menjadi arena adu cepat dan adu keras. Media sosial yang mestinya wadah berbagi informasi malah menjadi gelanggang duel ego. Siapa yang paling keras berteriak sering dianggap paling benar. Padahal, dalam kebijakan publik, kebenaran tidak diukur dari seberapa viral sebuah pernyataan, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan setelah diuji fakta.
Pagar Bernama Kepakaran
Matinya Kepakaran mengingatkan, menghargai ahli bukan berarti menelan mentah-mentah semua ucapannya. Artinya, kita memahami bahwa proses ilmiah, akumulasi pengetahuan, dan pengalaman adalah pagar agar kita tidak tersesat. Di era ketika opini bisa “disulap” menjadi fakta hanya lewat jumlah share, rasa ragu yang sehat adalah satu-satunya pelindung.
Agustus 2025, Indonesia berdiri di persimpangan. Di satu jalur, ada upaya memperkuat literasi, mengembangkan teknologi, dan membangun kebijakan berbasis data. Di jalur lain, ada arus besar yang percaya pada kecepatan viral lebih daripada kedalaman analisis. Pilihan jalur ini akan menentukan kualitas peradaban kita di masa depan.
Dalam prasmanan kebenaran, hidangan yang sehat jarang jadi favorit. Makanan manis dan pedas lebih cepat ludes. Begitu juga dengan informasi: narasi emosional dan sensasional lebih cepat menyebar daripada fakta yang hambar di mata sebagian orang. Padahal, justru fakta-fakta “hambar” inilah yang sering menjadi pondasi kebijakan yang benar.
Di negeri yang dijuluki “gelap”, bukan lampunya yang padam, melainkan pikiran yang membeku. Buku Nichols ini bukan ajakan membela “orang pintar” semata, tetapi seruan untuk menyalakan kembali lampu refleksi. Sebab, tanpa akal sehat, kita hanya menjadi tamu prasmanan yang mengisi piring dengan apa pun yang terlihat menarik, tanpa sadar mungkin itu beracun.
Itulah peringatan Tom Nichols dalam The Death of Expertise. Menurutnya, kepakaran tidak mati karena orang awam kekurangan akses informasi, tetapi karena banyak yang menolak otoritas ilmiah dan memilih opini sesuai keyakinan. Hasilnya? Kebenaran sering kalah oleh suara paling keras.
Tantangan ini juga berlaku bagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang sejak awal berdiri membawa misi mencerdaskan bangsa melalui dakwah, ilmu, dan gerakan kritis. IMM seharusnya menjadi benteng terakhir tradisi berpikir sehat di tengah riuhnya opini agar arah gerak bangsa ditentukan bukan oleh yang paling nyaring, tetapi oleh kebenaran yang teruji. (*)
Editor ‘Alimah Qurrota Ayun



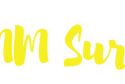
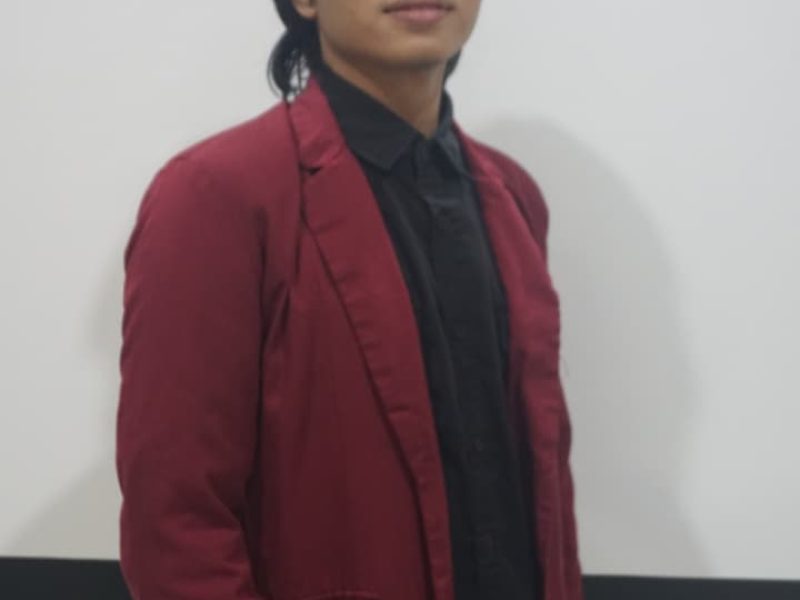
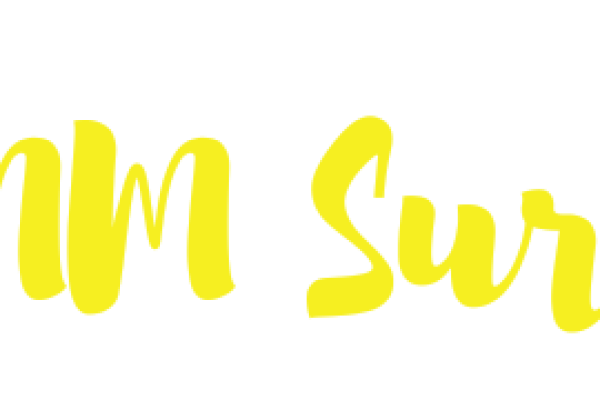
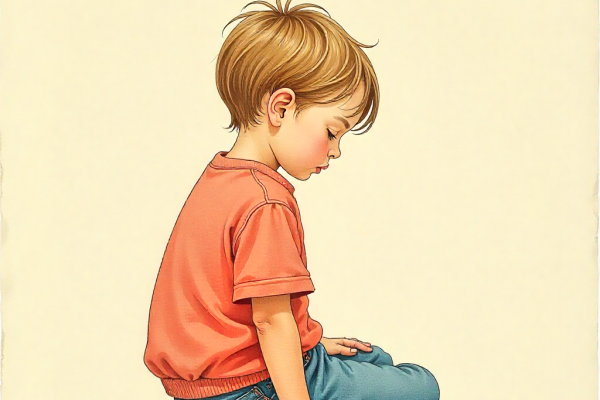



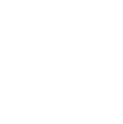
1 Comment
Your blog has quickly become one of my favorites. Your writing is both insightful and thought-provoking, and I always come away from your posts feeling inspired. Keep up the phenomenal work!