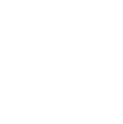Oleh: M. Ubaidillah Masrur, Bendahara Umum PC IMM Kota Surabaya
Surabaya – Akhir-akhir ini saya merasa kesal dengan konten-konten promosi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) di media sosial yang menggunakan siswi cantik dan siswa ganteng sebagai ikon promosi sekolah. Menurut saya mereka cenderung memandang dan menjadikan siswa sebagai objek visual, bukan subjek yang dihargai karena intelektualitas atau prestasinya.
Hal tersebut dilakukan semata-mata mengejar tren atau jumlah views dari media. Ini bukan hanya problem etika saja, tapi juga berisiko mendorong normalisasi standar kecantikan tertentu, yang mampu mempengaruhi kepercayaan diri siswa lain.
Saya pun teringat dengan teori male gaze yang dikembangkan oleh Laura Mulvey (1975), serta konsep objekifikasi dalam visualitas. Teori male gaze (tatapan laki-laki) menjelaskan perempuan dalam media sering dikonstruksi sebagai objek visual yang dinikmati dari sudut pandang laki-laki. Secara tidak langsung membagi pandangan menjadi dua yaitu, aktif (laki-laki) dan pasif (perempuan). Laki-laki menjadi spectator (penonton) sedangkan perempuan menjadi spectacle (tontonan). (Astuti et al., 2024)
Dalam konteks promosi SPMB, ketika siswi ditampilkan sebagai figur yang menarik secara fisik dan digambarkan dalam tarian-tarian, maka mereka secara sadar atau tidak telah dijadikan objek dari tatapan (gaze). Tak hanya siswi, para siswa pun juga mulai terkena dampak dari estetika visual ini. Wajah rupawan, gaya berpakaian trendi, dan postur tubuh tertentu menjadi standar yang dipromosikan sebagai “representasi siswa ideal”. Padahal, promosi semacam ini justru mempersempit makna ‘ideal’ menjadi semata-mata visual dan performatif.
Dalam kerangka budaya tatapan, konten promosi SPMB dapat disebut sedang melayani hasrat melihat. Penonton konten menjadi “penikmat visual”, sementara siswa-siswi menjadi objek “yang ditatap” dan kehilangan subjektivitas-nya sebagai pelajar. Ketika siswa-siswi ditampilkan bukan karena prestasi, tapi karena bisa menjual citra, maka institusi pendidikan tidak hanya sedang membangun citra palsu, tapi juga turut memperkuat budaya lookism (diskriminasi berbasis penampilan).
Semiotika Roland Barthes
Mari kita coba gunakan metode semiotika Roland Barthes untuk menganalisis konten tersebut. dalam metode semiotika barthes, setiap gambar atau aksi mengandung penanda (signifier) dan petanda (signified). Dalam konteks video promosi SPMB:
- Penanda: Siswi cantik dan siswa ganteng sedang berjoget dengan seragam sekolah, senyum ceria, gerakan mengikuti tren kekinian yang sedang ada di media sosial.
- Petanda: Sekolah terlihat asyik, modern, gaul, tidak kaku, dan mengikuti zaman.
Coba kita pikirkan ketika ini dikonsumsi secara luas di ruang publik, tanda ini berubah menjadi sebuah mitos: sekolah yang baik adalah sekolah yang estetik secara visual, penuh keceriaan performatif, dan mampu mengikuti zaman dan tren. Dalam kerangka Barthes, mitos adalah bentuk ideologi yang terselubung dalam tampilan sehari-hari. Mitos tidak tampil sebagai ideologi, tetapi sebagai sesuatu yang alami. Maka ketika siswa ganteng dan siswi cantik dijadikan wajah promosi, terciptalah mitos baru: penampilan fisik dan hiburan adalah representasi nilai institusi pendidikan.
Ini adalah bentuk pengaburan makna. Pendidikan tidak lagi dibaca sebagai proses intelektual dan etis, tetapi sebagai “pengalaman visual” yang menyenangkan. walaupun permukaannya saja. Tubuh siswi cantik dan siswa ganteng menjadi simbol dalam semiotika visual. Mereka tidak tampil sebagai individu yang utuh, melainkan sebagai ikon pemasaran. Wajah dan tubuh mereka bekerja sebagai penanda yang terus-menerus ditautkan pada kesan positif terhadap sekolah.
Tampilan Visual
Namun, dalam praktiknya, simbol ini menyingkirkan makna yang lebih dalam tentang keberagaman, kecerdasan, dan karakter siswa yang tidak tampil secara visual. Simbol tubuh ideal menjadi alat untuk menyampaikan pesan: “Ini sekolah modern, kekinian, dan kamu akan betah di sini” padahal yang disorot hanyalah citra, bukan substansi. Kita dapat memperluas analisis ini dengan menyentuh konsep simulacra dari Baudrillard: ketika representasi tidak lagi menunjuk pada kenyataan, melainkan pada “realitas palsu” yang diulang-ulang.
Promosi yang hanya menampilkan siswa ganteng dan siswi cantik menjadi simulasi dari “keceriaan dan keindahan sekolah”, padahal tidak ada jaminan bahwa budaya belajar di dalamnya mencerminkan hal itu. Video tersebut bukan lagi sekadar promosi, tapi menjadi hiper-realitas. di mana yang ditonton bukanlah sekolah. melainkan impian atau citra yang diinginkan tentang sekolah.
Hal tersebut wajar dilakukan, karena kita sedang hidup dalam budaya visual didorong oleh algoritma. Dalam logika media sosial, visual yang menarik seringkali berwujud tubuh dan wajah. Hal semacam itu lebih mudah viral dibandingkan konten yang informatif atau intelektual. Sekolah-sekolah pun ikut terjebak dalam budaya ini dan berisiko mengalihkan fungsi utamanya sebagai ruang pendidikan menjadi panggung pertunjukan citra.
Namun, apabila promosi sekolah hanya menekankan “visual” tanpa konteks edukatif, maka pesan yang diterima publik bisa jadi citra lebih penting daripada isi. Ini menciptakan relasi kuasa visual yang timpang, di mana siapa yang menarik akan ditampilkan, dan yang tidak dimunculkan dalam narasi. Akankah kita tetap terjebak? Mungkin saja. (*)